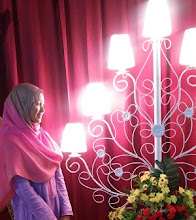Pantai Siring Kemuning Pamekasan tempatku tinggal. Hidup di pantai sungguh menyenangkan. Gemuruh ombak dan kicauan burung pantai selalu damai terdengar sebagai musik pembuka setiap pagi dan kadang membuat ‘galau’ jika musim hujan begini. Hati was-was akan datangnya badai tanpa diduga-duga. Membayangkan rumah hanyut bersama air mata yang tiada artinya jika tak punya cukup modal ketegaran.
Suasana petang yang mencekam, angin
terdengar jelas berhembus di sela-sela ribuan rintik hujan disertai petir yang
menggelegar memekakkan telinga. Terdengar suara sayup-sayup emak memanggilku
dari arah dapur.
“Lela, mareh e yangkes bujennah gellek?” (Lela, sudah diambil garamnya tadi?).
Pertanyaan itu membuatku harus menepuk
keningku sendiri. Lagi-lagi lupa! Tadi pagi emak memintaku untuk mengamankan
garam yang sedang dijemur jika hujan datang. Tanpa menjawab panggilan emak, aku
menghampiri tempat garam itu dijemur. Dugaanku benar, garam itu telah meleleh
tersentuh air hujan yang begitu derasnya. Dengan wajah pucat pasi aku
menghampiri emak yang sedang memasak nasi goreng. Suaraku pelan dan gemetar.
“Kuleh keloppaen, seporannah giy, Mak.” (Saya lupa mak, maaf ya, Mak)
Emak batuk kecil kemudian tersenyum tanda
memaafkan, tapi aku tahu pasti dia tak ingin melihatku bersedih. Aku melahap
nasi goreng bersama emak dan bapak dengan perasaan sedikit canggung karena
kejadian tadi. Namun emak berusaha tenang menutupi musibah tadi di depan bapak.
Suasana
pantai di sore hari membuat hati damai, gemericik ombak yang sedang surut
bersahut-sahutan. Mega merah bertengger di ufuk barat mengintip dunia, aku tak
ada pekerjaan lain selain membantu emak memasukkan kembali garam yang telah
dijemur kedalam rumah. Begitu setiap harinya.
Man
Suleman datang membawa berkat yang telah memenuhi tangannya. Beliau menghampiri
aku dan emak yang sedang duduk menikmati semilir angin pantai.
“Napah
gnikah, Man?” (apa itu, Man?) tanyaku penasaran
“Bedeh
titipan derih Man Ja’far gellek, seporannah skunnik.” (ada sedikit titipan
dari Paman Ja’far) Jawab Man Suleman
“Bedeh
napah e compo’en Man Ja’far?” (ada acara apa di rumahnya Man Ja’far?)
“Konjengan,
Bibul a sonnat” (Hajatan, Bibul sunnat)
“Keso’on,
Man”(terima kasih, Man)
Aku
meraih berkat itu dan mulai membukanya bersama emak. Emak masuk ke dalam mencari
bapak. Kemudian keluar lagi. Tak ku lihat ada bapak di belakangnya.
“Kammah
bapak, Mak? Toreh de’er bereng.” (mana bapak, Mak? Ayo makan bareng)
“Bapak
tedung mloloh, jhek gellek se tedung, la tedung poleh.” (bapak tidur
melulu, tadi udah tidur malah tidur lagi)
Kamipun
makan berkat tadi berdua. Ayam panggang, lezat sekali. Perut terasa sesak,
tidak kuat untuk berdiri saking kenyangnya.
Terdengar suara Man Qohhar menjajakan sate supernya
dengan mengayuh gerobak sate itu. Sate Man Qohhar terkenal dengan bumbu
kacangnya yang lezat membuat perutku garuk-garuk lagi.
“Satte..satte…bumbu kacang satte satte….sattenya,
Non.”
(sate..sate…bumbu kacang sate..satenya, Non) tawarnya kepadaku
“Yahh..Man Qohhar detheng telat. Lela pon
de’er ollennah konjengen.”(yahh.. Man Qohhar datang telat. lela udah makan dapat dari hajatan)
“Oye deh…da daa, Non… satte satte…”
...
Suatu hari, keluargaku kedatangan saudara
bapak dari Jawa, hanya bapak yang bisa berbincang-bincang dengan mereka
menggunakan bahasa jawa. Aku mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi aku tidak
bisa melafalkan dalam bahasa mereka. Lebih-lebih emak yang hanya bisa melihat
mereka bicara tanpa mengerti artinya. Sesekali bapak menerjemahkan omongan
mereka agar emak mengerti. Hanya anggukan-anggukan kecil sebagai respon dari
emak.
Mereka berkunjung ke Pulau Garam ini untuk
menghabiskan waktu liburan selama seminggu lamanya. Terpaksa aku menjadi pengarah
jalan dadakan, untungnya aku masih ingat meskipun sedikit jalan-jalan menuju
wisata di kota ini, berkat pengalamanku dulu waktu SMA bersama teman-teman
seperjuangan. Bila sekolah libur, langsung melancong ke tempat-tempat wisata
yang belum tentu banyak orang mengetahuinya ini. Kalau lagi banyak fulus
alias gajian dari hasil menjaga toko, langsung bareng-bareng wisata kuliner di dalam
kota yang penuh dengan ragam ciri khas ini. Bebek Sinjay makanan favorit
khas Bangkalan dan menjadi salah satu ikon Madura dalam kulinernya. Harga tidak
mahal bagi yang berduit, kalau bagiku, mendingan makan nasi pecel atau tempe
penyet saja kalau belum gajian.
Fajar telah nampak di ufuk timur, aku
terbangun dan segera mandi lalu shalat shubuh berjama’ah bersama keluargaku dan
keluarga paman. Rencananya, lepas shubuh kita akan berangkat melancong. Aku
sudah berias secantik mungkin, tapi tetap saja adikku yang paling bandel, Fandi
mengejek.
“Yu Lela paggun jubek.” (Mbak Lela tetap jelek)
“Iyeh, mun Yu jubek, Fandi sajen jubek.” (iya, kalau Yu jelek, Fandi tambah jelek)
Yu adalah panggilan untuk kakak perempuan
bagi orang Madura dan Cak panggilan untuk kakak laki-laki. Sedangkan panggilan
untuk adik laki-laki adalah Kacong dan Nik untuk adik perempuan.
“ciyuuuss?? Miepah?” sahut Fandi dengan centil.
“hahh?! Nak-kanak kinnik la ajer bahasa tak
genna yeh…jhek biasa agih, Cong.” (hahh?! Anak kecil kok sudah belajar bahasa yang nggak
beres ya…jangan dibiasakan, Cong.”
. Tiba-tiba datang Farhan, anak Man Sholeh
yang berumur sekitar 5 tahun dengan kaki setengah agak pincang seperti menahan
pipis. Mukanya terlihat kusut dan dahinya terlipat.
“Entarrah demmah, Cong?” (mau kemana, Cong?)
“Pundhi jedenge nggeh, Mbak?” (mana kamar mandinya ya, Mbak?)
Untuk kali ini aku benar-benar tidak tahu, apa
artinya bahasa jawa itu. Kayaknya sih itu bahasa jawa yang kromo inggil,
seingatku pada pelajaran bahasa daerah waktu SD. Tapi satu kata yang aku
tangkap, yaitu jeddeng sama dengan bahasaku yang artinya kamar mandi.
Tanpa pikir panjang, ku arahkan jariku pada kamar mandi yang terletak di sudut
rumah samping dapur itu. Farhan mengikuti arah tunjukku. Beragam corak bahasa
di negeri ini, menambah sensasi untuk lebih mendalami dari satu bahasa ke
bahasa lain.
“Yu
nikah de’remmah se, mun lah ajelen kattah a kemmiah ntar de’mah pole mun benni
ke jeddeng.” (Yu ini gimana sih, kalau berjalan seperti mau pipis gitu mau
kemana lagi kalau bukan ke kamar mandi) kata Fandi dengan gayanya yang sok tahu,
menyilangkan tangan di depan dadanya. Aku terkekeh melihat gayanya itu.
Mobil menderu memulai perjalanan yang
mungkin sangat panjang, parkir dari satu tempat ke tempat lain. Pemandangan
indah yang menarik mata, melewati sebuah area persawahan yang membentang luas
dengan udara pagi yang sejuk. Suara burung-burung bernyanyi indah meramaikan
bumi pertiwi.
Farhan jingrak-jingkrak dalam mobil melihat
seekor burung perkutut bertengger pada orang-orangan sawah yang kemudian
terbang karena orang-orangan tersebut bergoyang terterpa angin. Sawah
terbentang luas menghijaukan bumi gersang ini. Setelah setengah jam perjalanan,
sampailah aku pada pantai yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Pamekasan
dan Sumenep. Pohon cemara yang baris berjajar menambah kesejukan Pantai Talang
Siring ini.
Aku berjalan-jalan di sepanjang pantai
bersama Farhan dan Fandi layaknya emak yang menggandeng dua anaknya.
“Emak…emak…minta uang” rengek Fandi menggoda melihat mukaku yang
kusut
“Emak derih hongkong, gik ngodeh Yu nah,
Cong. Kedih la engak emak-emak.” (emak dari hongkong, Yu nya masih muda, Cong. Masak
sudah kayak emak-emak sih)
Ku lihat paman dan bibi asyik menikmati
keindahan pantai ini, sedangkan aku harus menjaga ekstra ketat pada dua anak
kecil ini agar tidak terlalu jauh bermain ombak.
Setelah berbasah-basah ria menjaga mereka, perjalanan
diteruskan ke Museum Kota Sumenep yang biasa dikenal dengan Museum Kraton. Satu
jam kemudian, sampailah aku pada Museum yang mempunyai keunikan ini. Bagaimana
tidak, Al-Qur’an dengan tinggi 4 meter dan lebar 3 meter dengan berat 500
kilogram terdapat di Museum ini. Konon, Al-Qur’an yang ditulis oleh Raja
Sumenep, Sultan Abdur Rahman Pakuningrat hanya dalam waktu satu malam
menggunakan tinta Kallam yaitu asap dari lampu tempel, sedangkan alat tulisnya
menggunakan bulu ayam.
“Lela, ayo mudun. Ngopo ngelamun ndek kono?” (Lela, ayo turun. Ngapain ngelamun di situ?)
kata Man sholeh membuyarkan lamunanku. Aku garuk-garuk kepala yang tidak terasa
gatal sama sakali meski kata emak kutu yang bersemayam dalam rambutku terhitung
banyak. Aku turun dan mulai memasuki museum ini. Terlihat rapi dengan
barang-barang unik dan kuno. Satu jam berputar-putar di museum ini, akhirnya
kami shalat dhuhur di sini dan mulai melanjutkan perjalanan.
Aku mengarahkan sopir ke sebuah pulau kecil.
Paman dan bibi hanya menurut saja. setengah jam kemudian, sampailah kami di
sebuah Pulau kecil yang terhitung sepi namun pemandangannya luar biasa
menakjubkan. Air laut yang biru dihiasi ombak-ombak kecil menambah keindahan
pulau kecil ini. Sewaktu SMA aku sering bermain-main kesini bersama
sekelompokanku. Pantai ini sungguh indah dan pas untuk menghabiskan waktu
rekreasi karena sejuk, rindang dan bersih karena memang belum terjamah oleh
kebanyakan orang.
Objek wisata ini belum ter-ekspos meluas,
hanya beberapa orang yang nampak menikmati keindahan alam ini. Menyayangkan
sekali. Pantai seindah ini tak dikenal orang. Pulau Kangean yang masih dalam
kabupaten Sumenep ini menyimpan banyak keindahan yang belum ter-ekspos media
sekalipun. Di sekitarnya terdapat pulau-pulau kecil yang tak kalah menarik
seperti Pulau Saular, Pulau Saredeng Kecil, Pulau Sitabbok, Pulau Sadular Besar
dan Pulau Saseel.
Sang mega merah telah bersiap menjemput
malam dan bergantilah hari menjadi petang. Karena terasa sangat lelah, kami
sekeluarga tertidur pulas di mobil sampai rumah. Lagi-lagi hujan turun di malam
hari. Kilat yang menyilaukan mata mengagetkanku disusul dengan petir yang
menyambar pohon kelapa di tengah hamparan sawah. Membuat mataku terbelalak dan
tak bisa terlelap kembali.
Emak dan
bapak tengah duduk di atas dipan sembari menyantap singkong goreng. Bibi
mengeluarkan plastik putih yang berisi makanan yang telah dibeli waktu di
Museum Keraton tadi siang. Kami berbincang-bincang dan bercerita tentang
melancong dalam sehari ini.
“Nik, lagguk bedheh Kerapan Sapeh e
Sampang.” (Nik, besok
ada Kerapan Sapi di Sampang) Kata emak sambil makan kerupuk dengan petis
“Enggiy, mak? Man Sholeh nyengo’ah napah
bunten?” (iya, Mak?
Man Sholeh mau lihat apa tidak?)
“iyo, ayo kesuk ndelok, Nduk” (iya, ayo besok lihat, Nduk)
Keesokan harinya, kami mulai bersiap-siap
menuju Kota Sampang tepatnya Lapangan untuk Kerapan Sapi yang berada pada
Kabupaten Sampang. Tujuan pertama pada hari kedua.
Terdengar orang-orang yang bersahut-sahutan
mendukung kerapannya masing-masing. Di sekeliling lapangan telah dipadati para
penonton kerapan sapi. Di sepanjang jalan terlihat kedai-kedai dan pedagang
kaki lima yang tak letih menjajakan pada siapa saja yang lewat di sampingnya,
rujak manis, rujak cingur, es dan snack-snack. Seorang bapak dengan kumis tebal
terlihat sibuk mempromosikan clurit yang dijualnya. Sebuah benda yang dikenal
sebagai senjata andalan orang Madura.
Kultur budaya yang masih kental melengkapi
keindahan pulau garam ini, segarnya udara dan beningnya air terjun Toroan jatuh
bebas ke laut lepas mencuci pikiran yang penat. Air terjun itu jatuh dan terus
jatuh tanpa henti menyisakan lumut-lumut hijau pada batu raksasa di sekitarnya.
Mungkin jika tidak hati-hati, orang akan terpeleset karenanya.
“Lela, sek ono piro wisata ndek Sampang iki?”(Lela, masih ada berapa wisata di Sampang ini?)
tanya bibi kepadaku. Aku sibuk menyisir rambutku yang basah terkena air
terjun tadi.
“Masih banyak, Bi. Kalau dijelajahi satu
persatu, bisa keok lho, Bi.” jawabku sambil terkekeh menggunakan bahasa Indonesia
dengan logat kemadura-maduraan. Membayangkan menjelajahi seluruh objek wisata Sampang,
pulang-pulang aku harus pijat kayaknya. Paman dan bibi menyambut jawabanku
dengan tertawa.
“Ono opo ae seng dorong?” (ada apa saja yang belum dikunjungi?) tanya
paman penasaran.
“Gua Macan Sampang, Gua Lebar Sampang,
Sumur Daksan Sampang. Apa lagi ya? Lupa deh, Man. Hehehe” jawabku dengan muka konyol.
Perjalanan pulang yang tak jauh beda dengan
kemarin, tulang serasa retak dan pisah dengan persendiannya. Di pikiranku hanya
terbayang nikmatnya tidur pada kasur dan bantal sambil memeluk jam weker hello
kitty pemberian emak. Aku kira sudah usai melancongku kali ini, ternyata mobil paman
merapat pada wisata Api Tak Kunjung Padam yang berada di Kabupatenku, Pamekasan
tepatnya di desa Tokol Kecamatan Tlanakan.
Mataku perlahan membuka sedikit, kantuk yang
telah menggelantung di pelupuk mata tak dapat aku enyahkan. Ku lihat dengan
mata sipit nyala api itu dari balik bingkai kaca mobil paman. Selanjutnya aku
terlelap terbang bersama mimpi-mimpi yang bercampur-baur.
“Farhan..!” teriakan bibi mengagetkanku hingga aku
kejedot sisi mobil. Aku langsung turun karena penasaran ingin melihat apa yang
sedang terjadi. Aku perhatikan bibi dengan tangkasnya menggendong Farhan yang
terlihat shock dengan apa yang telah dilakukannya. Ternyata Farhan
membuat lubang di sekitaran api itu dan lubang tersebut menyemburkan api
seperti lubang-lubang lainnya.
Cukup menarik perhatian, aku dan paman
mencoba membuat lubang di samping lubang api lainnya. Namun tak ada reaksi
munculnya api baru dalam lubang yang kami buat. Tiba-tiba muncul wanita tua
yang dikenal sebagai penjaga wisata Api Tak Kunjung Padam ini dan berkata,
“Percuma agebei lobeng makeh benyak mun e
sengaja” (percuma
membuat lubang kalau disengaja). Kamipun pulang dengan misteri keindahan di
hati masing-masing.
...
Harga mati, tak bisa ditawar. Aku tidur
dalam seharian ini, ketukan pintu emak nyaris tak terdengar. Kulirik jam yang
menempel di dinding kamar. Jam 14.10 WIB, aku loncat dari kasur dan segera
mengambil wudhu untuk shalat dhuhur. Membuka pintu dengan cepat dan segera
menyela omongan emak. “Lela bejengeh kadek, Mak.” (Lela shalat dulu,
Mak)
Usai shalat aku menghampiri emak yang
sedang berbincang-bincang dengan keluarga paman. Aku masih memakai mukena yang
menempel di badan, biar sekalian shalat ashar nanti pikirku. Aneh, keluarga paman
nampak bertambah satu. Ada Najih, putra sulung paman yang sedang kuliah di
Jakarta. “lho…menyusul ya, Najih? Sayang, udah setengah melancong ni.” sapaku
pada Najih yang kulihat sedang melihat ke arahku.
“Iya
nih, menyusul demi kerinduan pada pulau garam. Gimana usaha garamnya?”
“Sering
lupa kalau ada hujan, hahaha” seisi rumah tertawa terbahak-bahak.
...
“Hey Oreng medureh. Mayuh maen-maen ke
Suramadu…” (Hey Orang madura,
ayo main-main ke Suramadu) Ajak Najih dengan menirukan bahasa maduraku.
Nadanya terdengar aneh sehingga membuatku
tertawa karena dia memang tak pernah berbicara dengan bahasa Madura. “Mayuh
bos…”jawabku tergelak
Kamipun berangkat menyusuri desa-desa untuk
sekedar bermain-main di Suramadu, Jembatan indah yang menghubungkan Surabaya
dan Madura. Jembatan yang tergolong berusia muda karena selesai dan diresmikan
pada tahun 2010.
Kami mulai memasuki jembatan ini setelah
membayar karcis masuk Tol Suramadu yang hanya 3.000 rupiah untuk sepeda motor
dan 30.000 untuk mobil, sesaat kemudian sepeda melesat di atas jembatan yang
berangin cukup kencang itu.
“Najih,
percepat lajunya kalau nggak mau terbawa angin.”
“Iya,
Lela. Wah..seru sekali di Suramadu ini. Ambil foto yuk…”
“Yeee…biar
digiring sama Satpol PP ya…hahahaa.”
Setelah putar balik, kami mampir ke
stand-stand yang berjejer di pinggiran jalan. Banyak souvenir yang ditawarkan
di sana, mulai dari gantungan kunci, baju bertuliskan Suramadu, dan
makanan-makanan khas Madura.
Hari
terakhir keluarga Man Sholeh di rumahku, mereka mengajakku untuk wisata religi.
Inilah wisata yang aku suka, mengunjungi makam para Kyai dan membaca Al-Qur’an
di sana. Bukan niat menyembah tapi hanya mengharap barokah dari Kyai tersebut.
Selain Pulau Garam dan Tapal Kuda, Madura juga dikenal sebagai Daerah Santri
karena banyaknya Pondok Pesantren dan Kyai-Kyai besar yang tumbuh di Pulau ini.
“Orang Madura itu memiliki sebutan khusus
untuk para tokoh agama yaitu Bujuk. Istilah Bujuk biasanya dikaitkan dengan
nama tempat kyai itu berasal, kadang juga diambil dari kebiasaan Kyai saat
hidup. Seperti Bujuk Sangka yang berasal dari lokasi makamnya yang berada di
Desa Banyu Sangka, Kecamatan Tanjung Bumi- Bangkalan. Sementara nama asli dari Kyai
tersebut adalah Sayyid Husein.” Ceritaku panjang lebar pada Najih
“Bujuk itu kan yang di sudut ruangan itu
ya…?”
“Yeee..itu sih namanya pojok, Jih..hahaha”
Setelah menempuh perjalanan selama satu jam,
sampailah kami pada Makam Syaikhona Cholil yang berada di Kabupaten Bangkalan.
Seorang kyai yang dikenal dengan karomahnya, juga ilmu laddunni (ilmu
tanpa belajar) yang merupakan ma’unah dari Allah. Makam beliau telah
disesaki oleh para peziarah dari berbagai macam daerah. Akhirnya kamipun
mengambil posisi di pojok makan dan mengaji bersama.
Usai ziarah, keluarga pamanpun pulang
meskipun hujan turun dengan derasnya. Suara petir dan cahaya kilat bersahut-sahutan.
Aku pandangi mobil Man Sholeh yang semakin menjauh dan kemudian menghilang
tertelan bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jalan. Aku kembali teringat
pada sesuatu, Tang bujeh…!!! (garamku…!)